Imam di Ambang Hukum: Ketaatan Ganda Klerus Katolik antara Norma Kanonik dan Kewenangan Negara
Oleh: Rm. Yohanes Subani, Pr
Dalam bentangan tanah Timor yang kering namun subur oleh iman, identitas seorang imam Katolik bukan hanya terpahat oleh tahbisan suci, melainkan juga oleh kenyataan bahwa ia adalah warga negara dari sebuah komunitas hukum nasional. Dalam kerangka tersebut, seorang imam hidup dalam dinamika ketaatan ganda—taat kepada Allah dan Gereja-Nya, sekaligus tunduk pada hukum positif negara. Fenomena ketika seorang imam dipanggil oleh aparat penegak hukum sipil seringkali menimbulkan pertanyaan serius: Apakah ia bisa langsung memenuhi panggilan tersebut tanpa seizin otoritas Gereja?
Tulisan ini hendak menyelami norma hukum Gereja Katolik terkait keterlibatan klerus dalam proses hukum sipil, dengan memberikan sorotan khusus pada konteks pastoral, yuridis, dan kultural Bumi Timor. Dalam terang Hukum Kanonik, artikel ini juga berupaya memberikan pencerahan tentang perlunya dialog antara hukum Gereja dan hukum negara—sebuah panggilan untuk kolaborasi etis demi keadilan dan integritas pelayanan.
Kanon 285 §3: Perlindungan atas Martabat Imamat
Kitab Hukum Kanonik 1983 memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan atas imamat seorang imam dalam Kanon 285 §3: “Clerici ne partes assumant in causis civilibus, quae poenalem afferant sententiam, nisi de licentia Ordinarii sui” [1]. Norma ini melarang seorang klerikus untuk mengambil bagian dalam perkara sipil yang dapat berujung pada sanksi pidana tanpa izin eksplisit dari Ordinarisnya. Secara teologis dan pastoral, ketentuan ini tidak berfungsi untuk melindungi klerus dari hukum, tetapi untuk memastikan bahwa identitas dan misi imamat tetap utuh dalam sorotan publik dan proses peradilan.
Menurut Beal, larangan ini mencerminkan keprihatinan Gereja terhadap kemungkinan bahwa keterlibatan imam dalam proses pidana dapat menimbulkan skandal atau mengganggu persepsi umat terhadap pelayanan sakramental[2]. Oleh karena itu, izin dari Uskup bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari mekanisme Gereja dalam menjaga integritas pelayanan rohani dan publik seorang imam.
Otoritas Ordinaris sebagai Penjaga Integritas Pelayanan
Ketaatan klerikus kepada Uskup sebagai Ordinaris memiliki akar mendalam dalam spiritualitas dan struktur hierarkis Gereja Katolik[3]. Uskup bukan hanya atasan administratif, melainkan gembala dan penanggung jawab jiwa-jiwa para klerus dalam wilayah keuskupan.[4] Dalam konteks hukum, Ordinaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa imam yang dipanggil aparat hukum tidak diekspos secara tidak proporsional, dan bahwa hak-haknya sebagai rohaniwan tetap dihormati.[5]
Dalam dokumen Directory on the Ministry and Life of Priests (2013), Takhta Suci menyatakan bahwa jika seorang imam dipanggil untuk hadir di hadapan otoritas sipil, terutama dalam perkara pidana, ia harus terlebih dahulu memberitahu Ordinarisnya dan mengikuti arahannya[6]. Hal ini sejalan dengan semangat kolegialitas dan perlindungan terhadap kesejahteraan rohani dan jasmani klerus.
Dialog Hukum Gereja dan Hukum Negara
Di tengah semangat negara hukum dan supremasi hukum sipil, Gereja tidak bermaksud menempatkan klerus di atas hukum negara. Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan “Undang-undang sipil yang dirujuk oleh hukum Gereja harus ditepati dengan efek-efek yang sama dalam hukum kanonik, sejauh tidak bertentangan dengan hukum Ilahi dan kecuali ditentukan lain oleh hukum kanonik.”[7] Hukum Gereja menghormati hukum Sipil selama tidak bertentangan dengan hukum Ilahi dan moral Gereja. Klerus dapat tunduk pada hukum negara terutama dalam kasus pidana sipil seperti korupsi, kekerasan, pembunuhan atau penyalahgunaan kuasa yang dipercayakan kepadanya. Jika seorang klerus melakukan pelanggaran yang juga termasuk kejahatan pidana menurut hukum negara, maka Gereja tidak hanya menghukumnya secara kanonik tetapi bisa bekerjasama dengan otoristas sipil untuk penegakan hukum.[8] Sebagai warga negara, seorang klerus atau imam tidak dibebaskan dari hukum sipil, kecuali dalam hal yang menyangkut forum internal sacramental, misalnya pengakuan dosa umat beriman, tidak boleh dibocorkan meskipun diminta negara. [9] Gereja Katolik mendukung prinsip keadilan dan akuntabilitas. Namun, dalam kasus keterlibatan imam dalam proses hukum, Gereja memohon ruang untuk memastikan bahwa partisipasi tersebut tidak mengabaikan aspek pastoral, spiritual, dan institusional dari pelayanan Rohani seorang imam atau klerus.
Dalam konteks Indonesia, termasuk wilayah Nusa Tenggara Timur, penting adanya dialog konstruktif antara lembaga Gereja dan aparat hukum, demi terciptanya kerja sama yang sehat. Surat pengantar resmi dari Uskup kepada aparat hukum menjadi bagian dari etika komunikasi institusional yang mengedepankan penghargaan timbal balik antara dua otoritas: otoritas rohani dan otoritas sipil.
Pertemuan resmi dialogal antara pimpinan Gereja dan pimpinan penegak hukum negara akan membuahkan beberapa manfaat dalam kehidupan Bersama. Manfaat pertemuan resmi dialogal antara lain :
Pertama, Menjadi Model Sinergi Gereja-Negara di hadapan publik. Pertemuan ini mencerminkan kesadaran tanggungjawab Bersama dalam membangun Masyarakat adil, damai dan religious sesuai Pancasila, Undang-undang-undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Katolik. Selaian itu menjadi teladan kedewasaan dan perbedaan iman, ajaran moral dan dugaan konflik antaragama. Hal ini selaras dengan “Nota Kongregasi Iman (2004): Doctrinal Note on Participation of catholic in Political Life,” menegaskan hal tersebut:Gereja mendorong umat dan pemimpinnya berpartisipasi aktif dalam tata Masyarakat secara etis dan dialogis.
Kedua, Menjaga Asas Keadilan dan Prosedur Hukum yang Berimbang. Dalam pertemuan dialogal ordinaris wilayah dalam hal ini Uskup bisa mendapatkan klarifikasi resmi mengenai tuduhan yang dikenakan terhadap imamnya dan penegak hukum diberi kesempatan untuk menjelaskan proses hukum dan status hukum imam terlapor tersebut agar tidak ada manipulasi, kriminalisasi atau Tindakan yang bersifat politis. Inilah relevansi dari prinsip “due procces of Law” dalam hukum negara dan prinsip” ius in caritate”(hukum dalam Kasih) dalam Hukum Gereja.
Ketiga, Menjamin Perlindungan Hak Asasi dan Martabat Klerus. Seorang imam tetap memiliki hak sebagai pelayan Gereja termasuk hak atas pembelaan, pendampingan hukum dan praduga tak bersalah (presumption of innocence). Uskup sebagai otoritas gerejawi bertugas menjamin agar proses tidak mempermalukan Gereja atau menjatuhkan martabat pribadi seorang klerus secara publik tanpa dasar fakta dan hukum yang kuat. Gereja Katolik terus dan tetap mengajar tentang penghormatan terhadap martabat manusia dan proses hukum yang adil.[10]
Keempat, Menjaga Ketertipan Sosial dan Mencegah Provokasi Umat. Tuduhan penistaan agama bisa menyulut emosi publik. Dengan dialog resmi, Gereja dan apparat bisa mengelola informasi dan komunikasi publik secara tertip, mencegah hoaks atau hasutan orang yang tidak bertanggungjawab atau ingin memanfaatkan kesempatan untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompoknya. Gereja Katolik sejak semula tidak tertikat pada bentuk pemerintahan mana pun, tetap menjalin kerja sama sehat dengan negara dalam urusan Bersama demi kesejahteraan semua orang. [11]
Kelima, Menyatakan Sikap Kooperatif Gereja Terhadap Penegakan Hukum. Pimpinan Gereja dapat menegaskan bahwa Gereja tidak melindungi kesalahan, tetapi juga berhak membela kebenaran dan keadilan, termasuk perlindungan hak pelayannya. Hal ini memperkuat citra Gereja sebagai institusi yang taat hukum, namun tetap mempertahankan kedaulatan moral dan kanoniknya dalam menghadapi suatu persoalan hukum. Vos Estis Lux Mundi, mendorong kerja sama aktif Gereja dengan otoritas sipil dalam proses penegakan keadilan. [12]
Keenam, Menyiapkan Jalur Ganda: Proses Hukum Sipil dan Proses Hukum Kanonik. Bila setelah penyelidikan negara terbukti seorang imam memang bersalah secara hukum, Gereja wajib memprosesnya juga menurut norma hukum kanonik.[13] Bila imam ternyata tidak terbukti secara hukum, Uskup tetap melakukan evaluasi pastoral dan disipliner internal dengan para imam sebagai rekan sekerja dalam pelayanan pastoral secara berkala untuk membina, membimbing dan memperbaiki pelayanan klerus. [14]
Konteks Pastoral : Identitas Imamat dalam Komunitas Relasional
Imam-imam di bumi Timor dan di mana pun hidup dan berkarya, tidak berdiri dalam ruang kosong. Mereka hidup dalam jaringan relasi sosial yang kuat—terikat oleh adat, keluarga besar, serta tanggung jawab moral terhadap umat. Identitas imamat bersifat relasional, tidak bisa dijalani secara indivialistis, tetapi dalam komunio dengan klerus lain dan umat yang terikat oleh persaudaraan sacramental di antara mereka.[15] Ketika seorang imam dipanggil oleh polisi, bukan hanya dirinya yang terpanggil, tetapi juga seluruh identitas komunitasnya yang ikut serta dalam peristiwa itu. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas keterlibatan imam dalam proses pidana bukanlah proteksi personal, melainkan pelindung terhadap jalinan relasi suci antara imam dan umat beriman yang dilayaninya.
Pengalaman Gereja lokal menunjukkan bahwa pemanggilan seorang imam terlapor oleh otoritas sipil selalu didahului pemberitahuan kepada Uskup secara lisan dan tulisan . Dalam situasi kerja sama yang baik ini, menjadi sarana pastoral untuk meredam ketegangan dan menegaskan bahwa Gereja dan pemerintah hadir bersama umat dan masyarakatnya dalam menghadapi setiap persoalan hukum.
Penutup: Jalan Tengah Ketaatan dan Keadilan
Dalam dunia yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, Gereja tidak menutup diri dari proses hukum. Namun, Gereja juga menegaskan bahwa para pelayan Allah harus dijaga martabatnya, terlebih dalam menghadapi mekanisme peradilan sipil. Kanon 285 §3, beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya, menggarisbawahi bahwa kehadiran klerus dalam ranah hukum negara bukan semata soal hukum, melainkan juga soal pastoral, martabat, dan tanggung jawab bersama antara Gereja dan negara.
Dari tanah Timor yang setia, suara ini bergema: hukum Gereja dan hukum negara bukan dua kutub yang bertentangan, tetapi dua tangan yang bisa saling menggandeng untuk menghadirkan keadilan yang manusiawi, bermartabat, dan injili.
Daftar Pustaka
Beal, John P., James A. Coriden, dan Thomas J. Green. New Commentary on the Code of Canon Law. New York: Paulist Press, 2000.
Caparros, Ernest, et al. Exegetical Commentary on the Code of Canon Law. Montréal: Wilson & Lafleur, 2004.
Codex Iuris Canonici. Liber Secundus: De Populo Dei. Citta del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis, 1983.
Congregation for the Clergy. Directory on the Ministry and Life of Priests. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2013.
Congregation for the Clergy. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis: The Gift of the Priestly Vocation. Vatican City: LEV, 2016.
Dokumen Konsili Vatikan II
[1] Codex Iuris Canonici [CIC] 1983, canon. 285 §3.
[2] John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green, New Commentary on the Code of Canon Law (New York: Paulist Press, 2000), 375-376.
[3] Codex Iuris Cononici 1983, canon 273 381§1
[4] Codex Iuris Cononici 1983, 381§1; Dokumen Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja “Lumen Gentium(1964) Artikel 27
[5] Codex Iuris Cononici 1983, 392§§1-2; Apostolorum Successores (2024)-Instruksi tentang Pelayanan Uskup, Dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Para Uskup, Artikel 15; 20-21
[6] Congregation for the Clergy, Directory on the Ministry and Life of Priests, Vatican City, 2013, art. 26.
[7] Codex Iuris Cononici 1983, canon 22
[8][8] Codex Iuris Canonici 1983, Canon 1395§2; canon 1397; Motu Proprio: Vos Estis Lux Mundi (2019,revisi 2023),Artikel 19§§1-2
[9] Katekismus Gereja Katolik, Nomor 2240-2242
[10] Katekismus Gereja katolik, Nomor 1905-1912
[11] Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes, Artikel 76
[12] Vos Estis Lux Mundi, Artkel 19.
[13] Codex Iuris canonici, 1983, Canon1717-1719
[14] Codex Iuris canonici, 1983, Canon 384
[15] Codex Iuris canonici, 1983, Canon 275§1; canon 245§2; canon 529§§1-2; Paus Yohanes Paulus II, Pastores Dabo Vobis (1992), Artikel 17-18; 43-44; Directory on the Ministry and Life of Priests ( Kongregasi Klerus 2013), Artikel 38-41; Paus Fransiskus, Evangelii Gaudium, 2013, Artikel 24-33; 163-173; Paus Fransiskus, Christus Vivit, (2019), Artikel 203-212.
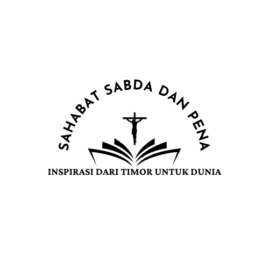
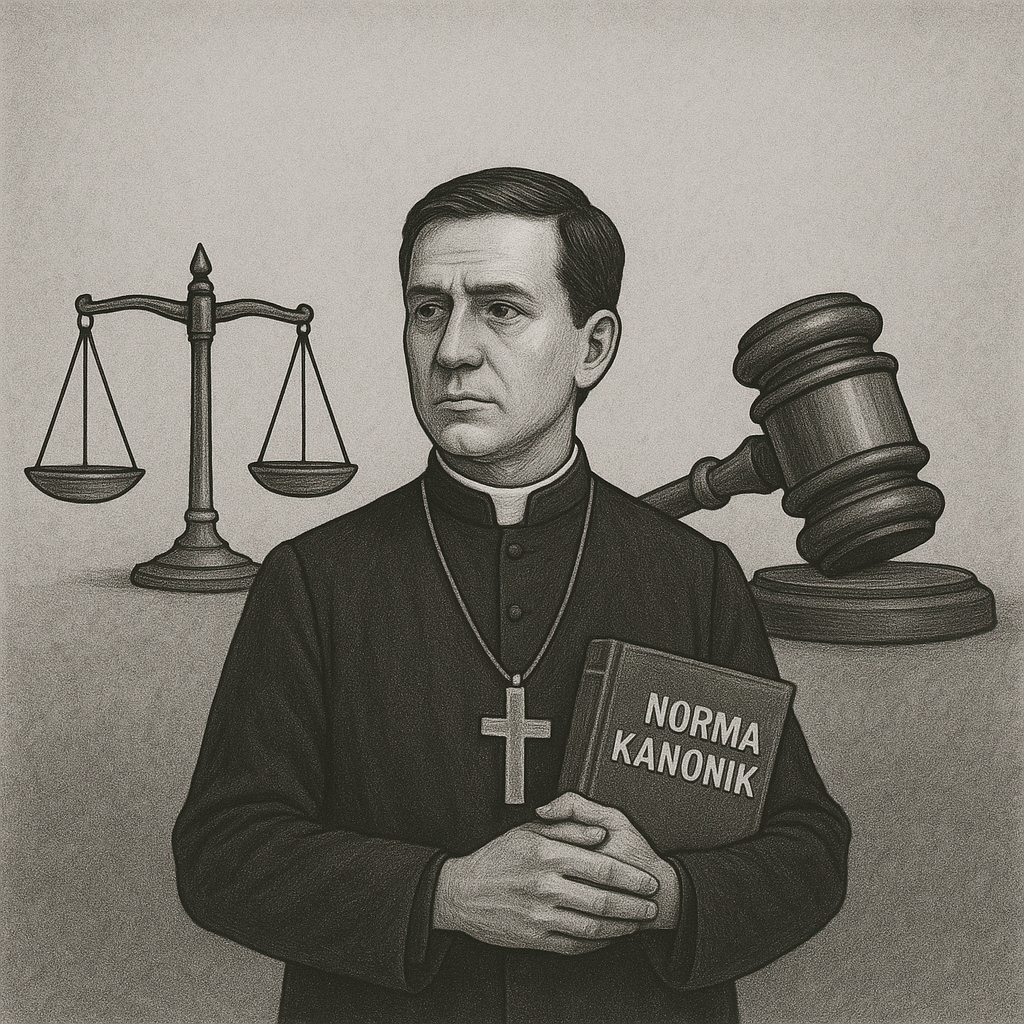
Terima Kasih Kakak Romo Jhon telah mencerahkan dengan tulisan tentang ketaatan Seorang Imam sebagai klerus sekaligus warga Negara, di hadapan hukum sipil dan hukum ilahi Gereja Katolik